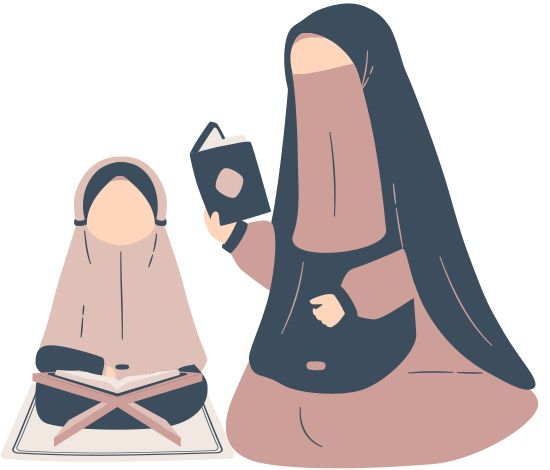Pertama Kali Mengajar Anak-anak TPA
Kisah Pertama Kali Saya Mengajar Ngaji Anak-Anak TPA
Hari itu langit sore berwarna jingga keemasan, angin berhembus lembut, dan suara anak-anak mulai terdengar dari surau kecil di ujung gang. Itulah hari pertama saya mengajar ngaji anak-anak TPA. Meski tampak tenang di luar, di dalam hati saya ada rasa gugup, campur aduk antara bahagia dan cemas.
Saya berdiri di depan pintu surau dengan mushaf Al-Qur’an di tangan, mencoba meyakinkan diri. “Bismillah,” ucapku pelan. Anak-anak duduk berderet di atas tikar, sebagian sudah membuka iqra', sebagian lagi sibuk bercanda. Mereka menoleh saat saya masuk, dan saya menjawab salam mereka dengan senyum yang sedikit kaku.
Saya memperkenalkan diri dengan suara yang sedikit gemetar. Ada anak-anak yang menyimak dengan wajah polos dan antusias, tapi ada juga yang tampak bosan atau malah bermain dengan temannya. Di situlah saya sadar: mengajar ngaji bukan hanya soal membaca huruf hijaiyah, tapi juga tentang memahami dunia anak-anak, sabar menghadapi tingkah mereka, dan tulus dalam menyampaikan ilmu.
Satu per satu anak saya panggil untuk membaca. Ada yang lancar, ada yang masih terbata-bata, bahkan ada yang belum bisa mengenal huruf sama sekali. Tapi saat mereka memandang saya dengan mata penuh harap, hati saya terasa hangat. Rasa lelah dan gugup perlahan hilang tergantikan oleh semangat.
Saya mencoba mengajar dengan suara lembut, sesekali diselingi cerita singkat agar mereka tidak bosan. Saat ada satu anak berhasil membaca dengan benar, saya beri pujian dan mereka tersenyum malu-malu itu momen yang paling membekas di hati saya.
Di akhir waktu, saya menutup dengan doa bersama. Anak-anak mengucapkan "terima kasih, Ustaz/ustazah" dengan kompak. Hati saya nyaris meleleh. Dalam perjalanan pulang, saya tersenyum sendiri.
Hari itu, saya belajar sesuatu: mengajar ngaji bukan hanya memberi ilmu, tapi juga menyentuh hati dan membentuk karakter. Hari itu bukan hanya hari pertama saya mengajar, tapi juga hari pertama saya jatuh cinta pada dunia berbagi ilmu.
Kisah di Bulan Ramadan: Haru di Tengah Cahaya Senja
Ramadan pertama saya bersama anak-anak TPA menjadi pengalaman yang tak pernah saya lupakan. Sejak awal bulan suci itu, suasana di surau terasa berbeda. Wajah-wajah kecil itu tampak lebih ceria, meski kadang lelah karena berpuasa. Tapi semangat mereka belajar mengaji justru makin tinggi.
Kami sepakat untuk menambah waktu belajar selama Ramadan. Selain membaca Al-Qur’an, saya mulai memperkenalkan tadabbur ayat secara sederhana. Saya ajak mereka merenungi makna ayat-ayat ringan, seperti tentang kasih sayang Allah, tentang sabar, dan tentang keindahan berbagi.
Satu sore, setelah sesi mengaji, saya membawa makanan ringan untuk berbuka bersama. Hanya sekadar kolak pisang dan teh manis, tapi anak-anak menyambutnya dengan senyum lebar.
Menjelang maghrib, kami duduk melingkar. Saya melihat wajah-wajah mungil itu menahan lapar dan haus, tapi tetap ceria. Saat adzan berkumandang, suara mereka serentak membaca doa berbuka, “Allahumma lakasumtu...”suara yang begitu polos, tapi menggema sampai ke hati saya.
Di hari ke-20 Ramadan, kami mengadakan acara pesantren kilat kecil. Anak-anak tampil membaca surat pendek, adzan, dan bahkan ada yang berani ceramah singkat di depan teman-temannya. Saat itu saya hampir menangis, melihat mereka tumbuh percaya diri dan makin cinta pada agamanya.
Yang paling mengharukan adalah saat salah satu anak, Fadil, berdiri dan membaca Al-Qur’an tanpa terbata-bata untuk pertama kalinya. Beberapa bulan sebelumnya, ia bahkan belum bisa mengenali huruf hijaiyah. Hari itu, seluruh anak bertepuk tangan untuknya. Fadil tersenyum bangga dan saya menahan air mata.
Menjelang akhir Ramadan, kami mengadakan khataman kecil. Surau dihias sederhana, dan para orang tua hadir. Saya duduk di belakang sambil menyimak satu per satu anak membaca surat demi surat. Di antara lantunan ayat, hati saya penuh syukur. Bukan hanya karena mereka belajar, tapi karena saya ikut tumbuh bersama mereka.
Ramadan itu mengajarkan saya banyak hal: bahwa setiap huruf yang diajarkan adalah ladang pahala, bahwa ketulusan bisa mengubah semangat anak-anak, dan bahwa cinta pada Al-Qur’an tumbuh dari hal-hal kecil yang dilakukan dengan hati.
Di Balik Senyum dan Suara Anak-Anak: Tantangan dan Keteguhan Hati
Meski banyak momen indah dan menyentuh, perjalanan mengajar anak-anak TPA juga dipenuhi tantangan yang diam-diam menguji kesabaran dan niat saya.
Suatu waktu, saya sempat merasa lelah secara mental. Bukan karena anak-anak, tapi karena tekanan dari luar pekerjaan lain yang menumpuk, urusan rumah yang tak pernah habis, dan kadang suara-suara yang meragukan.
Ada yang bertanya, “Ngajar ngaji itu dibayar berapa sih? Apa nggak capek ngurusin anak-anak kecil tiap sore?” Saya hanya bisa tersenyum. Mereka tak tahu bahwa bukan uang yang saya cari, tapi keberkahan. Tapi tetap saja, kadang hati ini goyah.
Pernah juga saya merasa sedih karena ada anak yang berhenti datang. Setelah saya cari tahu, ternyata orang tuanya memutuskan memindahkannya karena merasa anaknya belum cukup cepat mengaji. Saat itu saya merasa gagal. Tapi saya belajar untuk tidak menyalahkan siapa pun, dan terus memperbaiki cara mengajar saya.
Namun, di balik semua itu, banyak juga orang tua yang mendukung sepenuh hati. Ada ibu-ibu yang datang khusus untuk mengucapkan terima kasih karena anaknya mulai semangat shalat. Ada bapak-bapak yang diam-diam meletakkan sekantong air minum atau jajanan di surau sebagai bentuk perhatian.
Saya teringat satu malam, ketika hujan deras mengguyur kampung. Saya hampir tak datang ke TPA karena jalan becek dan licin. Tapi sesampainya di surau, saya lihat lima anak duduk menunggu, kakinya basah, tapi mereka tersenyum. “Ustazah datang juga ya!” kata mereka.
Itulah hari ketika saya benar-benar merasa bahwa tugas ini bukan sekadar rutinitas. Ini adalah amanah. Berat, tapi indah.
Setiap tantangan datang dengan pelajaran. Dan setiap senyum anak-anak adalah pengingat, bahwa dalam dunia yang semakin bising ini, masih ada cahaya yang bisa kita nyalakan, meski kecil.
Mimpi Kecil Mereka, Harapan Besar Saya
Di sela-sela waktu belajar, sering kali anak-anak datang menghampiri saya hanya untuk bercerita. Bukan tentang huruf hijaiyah atau tajwid, tapi tentang dunia mereka yang polos, jujur, dan penuh harapan.
“Aku pengen jadi ustaz kayak Ustazah,” kata Aisyah sambil tersipu.
“Aku mau hafal Qur’an biar bisa bawain ibu ke Mekah,” ucap Farhan dengan mata bersinar.
“Aku mau punya rumah buat ngajarin anak-anak ngaji gratis,” kata Fadil dengan suara kecil tapi yakin.
Setiap kali mereka berkata begitu, saya diam. Bukan karena tidak tahu harus membalas apa, tapi karena hati saya sering tergetar oleh ketulusan mereka. Anak-anak ini bukan hanya sedang belajar membaca Al-Qur’an mereka sedang menanam benih impian yang mungkin akan tumbuh jadi pohon kebaikan di masa depan.
Saya tahu tidak semua dari mereka akan tumbuh dalam kemudahan. Ada yang pulang ke rumah sempit, ada yang makan seadanya, dan ada pula yang harus membantu orang tuanya bekerja sejak kecil. Tapi saya ingin mereka tahu, bahwa di surau kecil ini, mereka dicintai. Bahwa setiap ayat yang mereka baca adalah cahaya yang akan menuntun langkah mereka nanti.
Harapan saya sebagai pengajar sederhana:
Saya ingin mereka mencintai Al-Qur’an bukan karena paksaan, tapi karena merasa dekat dengannya.
Saya ingin mereka mengenang masa kecil di TPA ini sebagai masa yang indah dan hangat.
Saya ingin mereka tumbuh jadi anak-anak yang membawa cahaya di mana pun mereka berada.
Dan satu lagi saya ingin tetap ada untuk mereka. Meski waktu terus berjalan, meski hidup berubah, saya ingin tetap menjadi seseorang yang pernah hadir di perjalanan awal mereka mengenal kalam Allah.
Mengajar mereka adalah perjalanan jiwa. Saya belajar mencintai tanpa syarat, memberi tanpa pamrih, dan percaya bahwa sekecil apa pun kebaikan yang ditanam, Allah pasti akan menumbuhkannya dengan cara-Nya sendiri.
Ketika Cinta Tumbuh Lewat Ayat-Ayat-Nya
Waktu terus berjalan. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Anak-anak yang dulu masih terbata-bata membaca, kini mulai lancar melantunkan surat demi surat. Ada yang hafal Juz ‘Amma, ada yang mulai belajar tajwid, dan ada juga yang semakin aktif membantu teman-temannya belajar.
Saya pun berubah bukan hanya sebagai pengajar, tapi sebagai manusia. Anak-anak itu mengajarkan saya arti sabar yang sesungguhnya. Tentang bagaimana cinta tak selalu datang dalam bentuk kata-kata, tapi bisa hadir lewat pelukan kecil, senyum malu-malu, atau ucapan polos: “Ustazah, doain aku ya…”
Dalam hati, saya selalu berdoa agar mereka tumbuh menjadi pribadi yang kuat, lembut, dan beriman. Dunia ini keras, tapi saya percaya, mereka akan jadi bagian dari orang-orang yang membawa kesejukan karena mereka tumbuh dengan ayat-ayat Allah di hati mereka.
Dan jika suatu hari mereka lupa siapa saya, itu tak masalah. Karena saya tidak mengajar untuk dikenang. Saya mengajar agar Al-Qur’an tetap hidup di hati mereka. Saya hanya ingin menjadi batu kecil yang ikut membangun jalan mereka menuju kebaikan.
Mungkin surau ini kecil. Tapi di dalamnya, ada cahaya yang tak pernah padam cahaya dari suara-suara kecil yang melantunkan firman Tuhan-Nya dengan penuh harap dan cinta
Kisah ini tak benar-benar selesai. Karena selama ada anak yang ingin belajar, selama ada hati yang tulus mengajar, kisah ini akan terus berlanjut dalam hidup, dalam amal, dan dalam doa.
Ketika Surau Kecil Menjadi Taman Cahaya
Waktu berjalan seperti aliran sungai yang tenang namun pasti. Tahun pertama berlalu, disusul tahun kedua. Kini, wajah-wajah anak-anak yang dulu masih bingung mengeja huruf hijaiyah, sudah semakin fasih membaca surat-surat panjang. Beberapa bahkan mulai menghafal, dan satu dua anak sudah bisa menjadi imam shalat di rumahnya sendiri.
Suatu hari, aku datang ke surau seperti biasa, membawa buku Iqra dan mushaf. Namun, kali ini suasananya berbeda. Anak-anak berdiri menyambutku dengan seikat bunga plastik dan kue sederhana di atas nampan. Mereka berkata serempak, “Terima kasih, Ustazah…”
Aku terdiam. Tak tahu harus menjawab apa. Aku hanya bisa tersenyum sambil menahan air mata.
Ternyata hari itu mereka sepakat mengadakan kejutan kecil karena "hari jadi" TPA kami yang ke-2. Bukan karena aku meminta, tapi karena mereka merasa surau itu sudah menjadi rumah kedua. Mereka bilang, “TPA ini bikin kami sayang sama Al-Qur’an. Kalau sore nggak ngaji, rasanya kayak ada yang hilang.”
Momen itu sangat menyentuhku.
Bukan karena pujian. Tapi karena ternyata benih-benih kecil yang ditanam dulu mulai tumbuh. Anak-anak itu, yang dulu sering ribut, lupa bawa Iqra, atau bahkan malas datang, kini menjadi anak-anak yang menunggu-nunggu waktu ngaji.
Perubahan yang Terjadi
Tak hanya di diri mereka lingkungan sekitar pun perlahan ikut berubah. Para orang tua yang dulu hanya mengantar, kini sering duduk di belakang, ikut mendengarkan. Bahkan beberapa ibu mulai belajar membaca Al-Qur’an kembali, karena terinspirasi anaknya.
Saya mulai tidak hanya mengajar anak-anak, tapi juga membimbing ibu-ibu dengan kelas sederhana seusai Maghrib. Kadang hanya satu dua orang, tapi niat mereka begitu kuat.
Dari yang awalnya malu berkata “alif,” kini mereka bangga bisa membaca satu ayat.
Refleksi dalam Sunyi
Setiap malam, ketika lelah datang dan tubuh ingin rebah, aku sering termenung. Kupikir ulang perjalanan ini. Semua berawal dari satu keputusan kecil untuk mengajar di surau kecil. Tapi dari sana, Allah mengalirkan begitu banyak kebaikan untuk mereka, juga untuk diriku.
Mengajar TPA bukan sekadar memberi ilmu, tapi juga menjadi saksi pertumbuhan iman yang pelan tapi nyata. Di situlah aku merasa hidupku lebih bermakna.
Kadang aku bertanya, “Sampai kapan aku bisa bertahan di sini?” Tapi setiap kali aku mendengar suara kecil mengucap, “Bismillahirrahmanirrahim,” hatiku kembali teguh.
Khataman Pertama: Air Mata di Ujung Ayat
Hari itu langit tampak cerah, meski di dalam hati aku menyimpan awan haru. Sudah dua tahun aku membersamai anak-anak di TPA ini, dan akhirnya, tibalah momen yang sangat kami tunggu: khataman Al-Qur’an pertama.
Anak-anak datang sejak pagi, memakai pakaian terbaik mereka. Ada yang memakai baju koko putih, jilbab warna pastel, dan sarung batik hadiah dari orang tua. Surau kecil kami disulap menjadi tempat yang lebih istimewa dihias dengan balon, hiasan kertas bertuliskan “Selamat Khataman Al-Qur’an”, dan aroma harum bunga pandan dari sajian tumpeng yang disiapkan ibu-ibu kampung.
Aku berdiri di sudut surau, memandangi mereka satu per satu. Tak terasa, air mata menetes.
“Aku bangga sama kalian,” ucapku pelan saat membuka acara.
Suasana haru menyelimuti surau ketika anak-anak bergiliran membaca ayat demi ayat. Suara mereka masih polos, kadang terbata, tapi jujur dan tulus. Orang tua duduk rapi di belakang, sebagian menahan tangis. Aku lihat seorang ibu menyeka air matanya saat anaknya membaca surat An-Naba dengan penuh percaya diri.
Yang membuatku semakin terenyuh adalah ketika mereka selesai membaca ayat terakhir, lalu serempak membaca doa khataman dengan suara lirih:
"Allahummarhamna bil Qur’an, waj‘alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah…"
Aku menunduk. Suara doa mereka seperti menembus relung hati. Di surau kecil itu, aku merasa seperti sedang menyaksikan cahaya yang tumbuh perlahan cahaya dari hati anak-anak yang sedang mulai mencintai Al-Qur’an.
Hadiah Tak Terbungkus
Di akhir acara, kami memberikan sertifikat sederhana dan hadiah kecil berupa mushaf dan tasbih. Tapi hadiah yang sesungguhnya justru datang dari mereka dari ucapan sederhana:
“Terima kasih, Ustazah… Kalau nggak ada TPA, aku nggak akan bisa baca Qur’an…”
Itu bukan hanya ungkapan syukur. Itu seperti pelukan untuk jiwaku.
Salah satu anak, Fadhil, maju dan berkata dengan suara gemetar, “Aku janji mau lanjut hafal. Nanti kalau sudah besar, aku mau ngajarin anak-anak juga…”
Aku hanya bisa mengangguk, tak mampu berkata apa-apa. Dalam hati, aku berkata, "Jika hanya satu dari kalian yang melanjutkan ini, maka semua perjuangan ini tak sia-sia."
Setelah Khataman: Bukan Akhir, Tapi Awal Baru
Khataman itu bukan akhir, tapi justru menjadi awal baru. Anak-anak semakin semangat. Beberapa mulai ingin menghafal lebih banyak, ada yang ingin ikut lomba MTQ, dan bahkan ada yang menawarkan diri membantu adik-adik yang baru mulai belajar Iqra.
Dari yang dulu hanya datang untuk belajar, kini mereka mulai belajar untuk memberi.
Sebagai pengajar, hatiku penuh syukur. Aku tahu, jalan ini panjang dan tak selalu mudah. Tapi aku juga tahu, selama ada cinta di hati, Allah akan terus memberi jalan.
Akhir yang Tenang, Tapi Tidak Pernah Benar-Benar Selesai
Waktu berjalan begitu cepat. Surau kecil itu telah menjadi saksi begitu banyak cerita tangis pertama anak yang susah membaca, tawa yang pecah saat kuis huruf hijaiyah, dan pelukan haru di acara khataman.
Tapi seperti semua hal indah di dunia ini, masa itu pun perlahan sampai pada ujungnya.
Hari itu aku berdiri lebih lama di depan surau. Angin sore mengusap pipiku lembut, seolah tahu bahwa aku sedang menahan perasaan yang sulit dijelaskan. Besok, aku harus berpindah kota karena urusan keluarga. Keputusan berat, tapi harus dijalani.
Aku sudah memberi tahu anak-anak dan orang tua mereka seminggu sebelumnya. Tapi tetap saja, perpisahan bukan hal yang mudah. Anak-anak berkumpul, membawa surat-surat kecil yang mereka tulis dengan tangan sendiri. Ada gambar hati, ada tulisan "Terima kasih Ustazah", ada pula yang menulis, "Jangan lupakan kami."
Satu per satu mereka memelukku. Tak semua menangis, tapi semua merasa kehilangan. Dan aku pun begitu.
"Ustazah, nanti siapa yang ngajarin kami?"
"Ustazah, boleh video call kalau aku mau tanya surat baru?"
"Kalau aku rindu, boleh aku buka mushaf dan bayangin Ustazah di sini ya?"
Hati ini terasa penuh sesak. Aku tidak bisa memberi janji muluk. Tapi aku berkata:
"Lanjutkan membaca Qur’an, ya. Kalau kalian terus belajar dan menjaga ayat-ayat Allah di hati, maka kita tidak pernah benar-benar berpisah. Karena Al-Qur’an akan mempertemukan kita lagi kalau bukan di dunia, insya Allah di akhirat nanti."
Aku melangkah pergi sambil menoleh sekali lagi ke surau kecil itu. Di sana, aku melihat cahaya yang tak terlihat oleh mata cahaya yang tumbuh dari cinta, doa, dan ilmu yang pernah dibagikan.
Dan Hidup pun Berlanjut
Aku mungkin tidak lagi mengajar mereka secara langsung, tapi kisah ini tetap hidup di dalam diri. Aku melanjutkan hidup di tempat baru, bertemu wajah-wajah baru, dan mungkin jika Allah izinkan memulai lagi dari Alif Ba Ta.
Tapi satu hal tak pernah berubah: hatiku akan selalu kembali ke surau kecil itu. Tempat di mana aku pertama kali belajar bahwa mengajar bukan tentang kepintaran, tapi tentang ketulusan.
Dan selama masih ada anak-anak yang ingin belajar, selama masih ada satu tangan yang membuka mushaf, aku percaya...
kisah ini belum benar-benar berakhir.
Catatan dari Seorang Pengajar TPA: Surat untuk Diriku Sendiri
Untuk diriku sendiri,
yang pernah berdiri di depan surau kecil itu dengan tangan gemetar,
yang pernah ragu namun tetap datang setiap sore,
yang pernah lelah, tapi tetap memilih bertahan karena cinta.
Aku ingin kau tahu,
bahwa setiap langkah kecil yang kau ambil menuju surau itu
bukan langkah yang sia-sia.
Setiap huruf yang kau ajarkan,
setiap senyuman yang kau bagi,
setiap air mata yang kau tahan saat mereka mulai lancar membaca...
semua itu akan kekal di langit, jika bukan di bumi.
Kau tak hanya mengajar,
kau menyentuh hati-hati kecil yang sedang mencari arah.
Dan meskipun kau telah pergi dari tempat itu,
cahaya yang kau nyalakan tidak padam.
Ia hidup di dada-dada kecil itu.
Di suara mereka yang kini lancar melafazkan ayat.
Di tangan mereka yang terbiasa membuka mushaf.
Di kaki mereka yang terbiasa melangkah ke surau,
meski tanpamu.
Dan jika suatu hari kau meragukan arti dari perjalananmu,
ingatlah:
mengajar bukan soal seberapa banyak yang kau tahu,
tapi seberapa tulus kau mau berbagi.
Jika satu anak saja bisa mencintai Al-Qur’an karena kehadiranmu,
maka engkau telah menang.
Bukan di hadapan manusia,
tapi di hadapan Tuhanmu.
Kini, kau mungkin tak lagi duduk di surau itu.Tapi hati dan doamu tetap mengajar.Dan itulah keabadian dari seorang guru:Ia boleh pergi, tapi ilmunya tinggal.Ia boleh diam, tapi amalnya berbicara.Ia mungkin terlupa,tapi namanya tercatat di tempat yang tak pernah salah mencatat.
Tamat.